Jejak Masalah Tata Ruang di Sulawesi Tenggara
Kegiatan tiga hari yang diselenggarakan di kantor Komunitas Teras ini diikuti oleh perwakilan dari WALHI, Puspaham, Komdes, Teras, RPS, dan Sagori dengan fasilitasi JKPP. Di hari pertama pelatihan dimulai dengan sesi refleksi pengalaman peserta, terungkap kompleksitas permasalahan tata ruang yang melanda hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara.
Gelo dari Sagori Kabupaten Bombana melaporkan ancaman serius terhadap ekosistem pesisir dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) akibat ekspansi pertambangan dan perkebunan yang diduga menyasar cadangan emas di kawasan konservasi. "Dari sisi kapasitas personil lembaga sangat kurang untuk melakukan kerja yang terkait dengan tata ruang. Pintu masuk dari semua kejahatan yang dilakukan pemerintah dengan korporasi adalah melalui penataan ruang," ungkap Gelo.

Di Konawe Selatan, Gian dari WALHI menghadapi kasus pelik dimana Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit PT Merbau Indrajaya terbit di atas lahan masyarakat yang telah bersertifikat. Ironisnya, masyarakat pemilik lahan tidak pernah menjual tanahnya kepada perusahaan, namun sertifikat mereka tidak terbaca di kantor Badan Pertanahan Nasional.
Sementara itu, Didi dari Puspaham di Konawe Utara masih berjuang mengatasi dampak lingkungan pascatambang di blok Mandiodo yang tidak pernah direklamasi perusahaan. Upaya pembentukan komunitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mendorong pemulihan lingkungan.
Tantangan Implementasi Kebijakan
Dhani dari Komdes Konawe Kepulauan menyoroti kontradiksi antara putusan hukum dan realitas lapangan. Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa masyarakat memenangkan gugatan terhadap izin pertambangan nikel di kawasan hutan produksi terbatas, aktivitas pertambangan tetap berjalan hingga kini.

Kasus serupa terjadi pada kawasan mangrove yang seharusnya masuk kawasan lindung, namun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dialokasikan untuk perkebunan. Akibatnya, masyarakat bebas menebang mangrove karena memiliki sertifikat penguasaan tanah, yang berujung pada abrasi pantai.
Alex dari RPS di Konawe Utara mengungkap ketidaktahuan masyarakat terhadap status lahan mereka. "Setelah mereka tahu, ternyata pemukiman mereka berada dalam kawasan hutan dan juga termasuk wilayah pertanian dan perkebunannya," kata Alex yang kini tergabung dalam Greenvoice untuk mengadvokasi perubahan RTRW Sulawesi Tenggara.
Dialog dengan Pemerintah: Antara Regulasi dan Realitas
Kehadiran narasumber dari Dinas Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas PU Tata Ruang memberikan perspektif pemerintah dalam merespons permasalahan yang dihadapi masyarakat sipil.
Bapak Jun dari Dinas Bappeda mengakui kompleksitas tantangan penataan ruang. "Ruang kita terbatas tidak pernah bertambah dan populasi meningkat terus, aktivitas manusia tidak terbatas karena itu perlu adanya tata ruang," jelasnya. Ia juga menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan.
Menanggapi kekhawatiran peserta terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Jun menyatakan bahwa regulasi tersebut memang menimbulkan kekhawatiran, namun di sisi lain diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. "Kita butuh investasi, pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, investasi meningkat tapi belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat," ungkapnya.
Proyek Strategis Nasional dan Dilema Pulau Kecil
Kasus Pulau Kabaena menjadi sorotan khusus dalam diskusi. Bapak Anis dari Dinas PU Tata Ruang menjelaskan bahwa sekitar 65 persen wilayah Kabaena masuk dalam kawasan pertambangan dengan masa izin 20 tahun yang masih berlaku. Status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) membuat proses perizinan dipermudah, meskipun bertentangan dengan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Dalam aturan PSN itu boleh melakukan atau dipermudah tapi tidak semua juga jika melanggar aturan," jelas Anis, sembari mengakui bahwa kebijakan ini telah berlangsung lama dan sulit diubah karena izin telah diterbitkan sebelum penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) pada tahun 2018.
Upaya Pengendalian dan Inovasi Kebijakan
Meski dihadapkan pada tantangan regulasi yang kompleks, pemerintah provinsi mengembangkan beberapa pendekatan inovatif. Salah satunya adalah penggunaan instrumen "ketentuan khusus" (ketsus) yang memungkinkan kawasan pertambangan dikembalikan ke fungsi awalnya setelah masa izin berakhir, berbeda dengan "pola ruang utama" yang bersifat permanen.
Untuk sektor pertanian, pemerintah mempertahankan penetapan Kawasan Pangan Berkelanjutan (KP2B) meskipun ada tekanan untuk dikonversi. "Kalau dia habiskan sawahnya silahkan saja tapi dia dipindahkan. Mana lebih besar masyarakat dapatkan 2 sampai 3 kali lipat irigasinya," jelas Jun mengenai mekanisme relokasi dalam kasus PT IPIP di Kolaka.
Akses Informasi dan Partisipasi Masyarakat
Salah satu kritik utama yang disampaikan peserta adalah sulitnya akses terhadap dokumen RTRW yang sedang dalam proses revisi. Kiki dari Komdes menyayangkan terbatasnya informasi dan minimnya proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen strategis ini.

Menanggapi hal tersebut, Bapak Jun berjanji akan membuka akses dokumen secara online setelah penetapan resmi. "Untuk sekarang karena proses penyusunan itu belum bisa dibuka hanya yang kalau kita undang pasti kita akan berikan dokumennya," jelasnya sembari menegaskan komitmen untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas setelah penetapan.
Putusan Mahkamah Agung dan Implementasinya
Kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/2023 terhadap RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi pembelajaran penting. Meskipun MA telah memutuskan bahwa Pulau Wawonii sebagai pulau kecil tidak boleh ada aktivitas pertambangan, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan administratif.
"Sebenarnya kami mau hapus tapi sebenarnya regulasinya masih ada, makanya pendekatan kita di ketsus. Kalau ESDM mencabut itu otomatis ketsusnya berlaku tidak boleh pertambangan," jelas Jun mengenai strategi implementasi putusan pengadilan.
Sekolah Advokasi Tata Ruang ini menjadi bukti pentingnya ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penataan ruang yang kompleks. Dengan harapan bahwa upaya ini dapat memberikan dampak positif dalam 2-3 tahun ke depan, para peserta berkomitmen untuk terus mengawal proses penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
Ruang: Bukan Sekadar Lahan
Di hari kedua rangkaian diskusi bertema keberlanjutan ruang hidup dan keadilan agraria, para peserta mendalami topik tentang Politik Ruang – sebuah konsep yang tidak hanya mengupas batas wilayah fisik, namun juga membedah bagaimana kekuasaan, ideologi, dan praktik keseharian saling berbenturan dan memproduksi ketimpangan.
Sesi ini dibuka dengan refleksi kritis dari pengalaman di lapangan, khususnya di Kabupaten Konawe Utara, yang kini menjadi laboratorium sosial penting dalam melihat dinamika ruang dan perubahan tata kelola wilayah.
Para peserta mendefinisikan ruang secara beragam namun saling melengkapi. Bagi sebagian, ruang adalah wilayah agraria yang digunakan dan dikelola secara sosial. Bagi yang lain, ruang merupakan batas hidup komunitas—baik fisik, kultural, maupun simbolik. Dari sini, muncul kesadaran bahwa ruang bukan sekadar lahan kosong yang bisa dialokasikan semena-mena, melainkan tempat kehidupan berlangsung, tempat nilai-nilai dijaga, dan tempat identitas diwariskan.
Namun, di balik itu semua, terdapat ketimpangan serius dalam penguasaan ruang. Tambang, kebun sawit, dan proyek-proyek besar masuk tanpa sepenuhnya mempertimbangkan struktur sosial dan kebudayaan lokal. Pemerintah, dalam banyak kasus, masih memandang ruang secara fisikalistik dan teknokratis, dengan mengabaikan elemen partisipatif dan historis masyarakat lokal.
“Saat masyarakat diminta memberi pendapat, apakah mereka benar-benar setara dalam perencanaan ruang?” tanya Imran dari Komunitas Teras. Ia menegaskan pentingnya memperbesar kapasitas masyarakat dalam dialog ruang, bukan sekadar menjadi penonton ketika ruang mereka dirancang oleh kekuasaan di atas kertas.
Ketimpangan dan Keberlanjutan
Diskusi semakin dalam saat persoalan ketimpangan penguasaan tanah diangkat. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi karena masuknya tambang, tapi juga akibat warisan struktur agraria yang timpang sejak lama. Sebelum tambang masuk, banyak masyarakat hanya memiliki 1-2 hektar tanah. Ketika tanah itu hilang atau dikelilingi oleh wilayah tambang, mereka terjebak dalam ketergantungan ekonomi yang rapuh.
“Sekarang banyak kepala keluarga harus pergi ke daerah lain demi ekonomi karena di kampung mereka sudah tidak ada lahan. Apakah itu yang disebut sejahtera?” ungkap Dhani dari Komdes.
Sementara itu, Hilma dari KPPJ menyoroti pentingnya menggunakan bahasa yang bisa menjembatani dialog antara masyarakat dan pemerintah. “Jangan marah-marah. Kita harus masuk ke bahasa mereka agar putusannya bisa kita arahkan,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya memisahkan zona pertambangan dengan wilayah kelola rakyat agar keberlanjutan kehidupan bisa tetap terjaga.
Politik Ruang dan Negara
Pada bagian akhir diskusi, isu politik ruang ditautkan dengan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah. Sejumlah regulasi yang dikutip—mulai dari PP 8/1953, PP 24/1997 hingga UU 1/2004—menunjukkan bahwa negara masih menempatkan diri sebagai pemilik penuh ruang, seperti warisan konsep domein verklaring di masa kolonial.
Akibatnya, tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat formal atau yang dikelola secara adat kerap diklaim sebagai milik negara. Hal ini diperparah dengan keberadaan Bank Tanah dan klaim atas hutan negara yang justru melanggengkan perampasan ruang hidup rakyat.
Menuju Politik Ruang yang Adil
Diskusi hari itu tidak hanya menyoroti masalah, tapi juga membuka harapan. Para peserta sepakat bahwa perlawanan terhadap ketimpangan ruang harus dimulai dari pemahaman kolektif dan penguatan posisi masyarakat dalam perencanaan ruang. Strategi advokasi harus dibangun secara cerdas, dengan memperkuat data lokal, membangun dialog yang strategis, dan mengembangkan pemahaman lintas ilmu dan sektor.
Ruang bukan sekadar tempat atau batas administratif. Ia adalah tempat hidup, tempat bermimpi, tempat mencipta masa depan. Ketika ruang dikuasai oleh logika tambang dan pasar, maka yang terjadi bukan sekadar perubahan lanskap, tapi juga pergeseran relasi kuasa yang bisa menggerus akar kehidupan masyarakat.
Hari terakhir pelatihan ini dibuka dengan sesi refleksi yang dipandu oleh Indah. Peserta diajak merenungi kembali perjalanan dua hari sebelumnya dengan menuliskan satu kata yang paling berkesan dalam lembar kertas, yang kemudian ditempel di panel bersama. Dalam suasana hangat, lembaran-lembaran tersebut dibaca acak, dan kata-kata seperti “ruang” dan “ketimpangan” memantik diskusi mendalam tentang esensi persoalan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing.
Beberapa peserta menyampaikan pemaknaannya terhadap kata “ruang”. Iskandar dari Puspaham menjelaskan bahwa ruang tidak hanya terbatas pada wilayah fisik seperti daratan, udara, dan laut, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang tak kasat mata. Didi dari Puspaham menambahkan bahwa ruang bisa dimanfaatkan dalam bentuk fisik maupun abstrak, termasuk secara sosial dan ekonomi. Sementara Alex dari RPS menyatakan bahwa ruang merupakan wilayah ekosistem dan interaksi kehidupan, sehingga pengertiannya sangat luas. Di sisi lain, ketika membahas “ketimpangan”, Kiki dari Komdes menyoroti ketidakadilan dalam penggunaan ruang, di mana kebijakan ruang masih didominasi oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Didi menyebut bahwa pemilik modal cenderung lebih diuntungkan dalam penguasaan ruang, dan Gelo dari Sagori menyatakan bahwa negara justru sering memberikan ruang kepada perusahaan, mengabaikan keadilan bagi masyarakat.
Setelah sesi refleksi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis yang dipandu oleh Riza dari KPPJ. Ia memaparkan isu-isu yang bisa dianalisis secara spasial terkait kebijakan tata ruang. Peserta diminta untuk mengusulkan topik-topik prioritas, dan muncul sejumlah saran. Kiki mengusulkan analisis menyeluruh karena semua aspek saling berkaitan. Iskandar mengarahkan fokus pada kawasan hutan dan pertambangan, sementara Gelo mengusulkan pembahasan yang lebih praktis, yakni terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH). Hilma dari KPPJ menambahkan pentingnya memperhatikan data mengenai kemiskinan dan potensi ancaman terhadap penghidupan masyarakat. Kesepakatan akhirnya mengerucut pada tiga tema utama: kondisi fisik wilayah, penguasaan tanah, dan potensi ancaman terhadap kawasan hutan.
Pelatihan kemudian memasuki sesi praktik pengumpulan dan analisis data spasial. Para peserta dibagi ke dalam dua kelompok dan diberi tugas untuk mengolah berbagai data, seperti pola ruang dalam draft RTRW, peta perizinan tambang, kehutanan, perkebunan, serta wilayah kelola masyarakat termasuk perhutanan sosial dan adat. Pengumpulan data dilakukan melalui platform bersama yang telah disediakan. Dalam proses ini, para peserta menggunakan software GIS untuk melakukan overlay dan intersect antara peta perizinan tambang dan dokumen tata ruang.
Temuan dari analisis spasial ini cukup mencengangkan. Dari hasil overlay, terungkap bahwa sebagian besar izin tambang tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi. Padahal secara regulasi, kawasan ini seharusnya memiliki perlindungan tertentu dari aktivitas ekstraktif. Tak hanya itu, wilayah perizinan tambang juga tumpang tindih dengan kawasan rawan bencana dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), yang mengindikasikan ancaman langsung terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Temuan ini diperkuat melalui penghitungan luas tumpang tindih menggunakan fitur pivot table pada perangkat lunak analisis data, di mana peserta membagi peran menjadi tim peta, tim tabel, dan tim narasi.
Hasil analisis ini kemudian dirangkum dalam presentasi slide, dimulai dari perbandingan konsistensi antara kawasan pertambangan dan pola ruang, dilanjutkan dengan overlay kawasan pertambangan dengan KP2B dan wilayah rawan bencana. Meskipun beberapa overlay tidak bisa dilanjutkan karena keterbatasan data, dua analisis utama—tambang versus pola ruang dan tambang versus kawasan rawan bencana—mampu memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kebijakan tata ruang saat ini mengabaikan aspek keselamatan lingkungan dan sosial.
Sebagai penutup, para peserta mempresentasikan narasi dari hasil analisis kelompok masing-masing. Narasi-narasi ini memperlihatkan betapa pentingnya penguasaan atas data dan peta dalam perjuangan merebut kembali ruang yang adil bagi masyarakat. Pelatihan hari ketiga ini bukan hanya menjadi momen teknis dalam memahami tata ruang, tetapi juga menjadi titik balik kesadaran bahwa perjuangan atas keadilan ruang harus disertai bukti, alat, dan strategi yang tepat. Seperti yang disampaikan Indah dalam sesi penutupnya, “Hari ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja-kerja panjang untuk memperjuangkan ruang hidup yang adil bagi semua.”
Harapan dan Rekomendasi
Sekolah Advokasi Tata Ruang ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk penguatan tata kelola ruang di Sulawesi Tenggara:
- Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil: Perlunya peningkatan kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam memahami dokumen teknis tata ruang dan melakukan advokasi berbasis data.
- Transparansi dan Partisipasi: Pembukaan akses informasi yang lebih luas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.
- Koordinasi Antar Sektor: Perlunya koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dalam implementasi kebijakan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
- Perlindungan Ekosistem Kritis: Penetapan kawasan-kawasan ekosistem penting seperti mangrove, hutan lindung, dan daerah aliran sungai sebagai area yang tidak dapat dialihfungsikan.
Mekanisme Penyelesaian Konflik: Pengembangan mekanisme yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik tata ruang, termasuk implementasi putusan pengadilan.



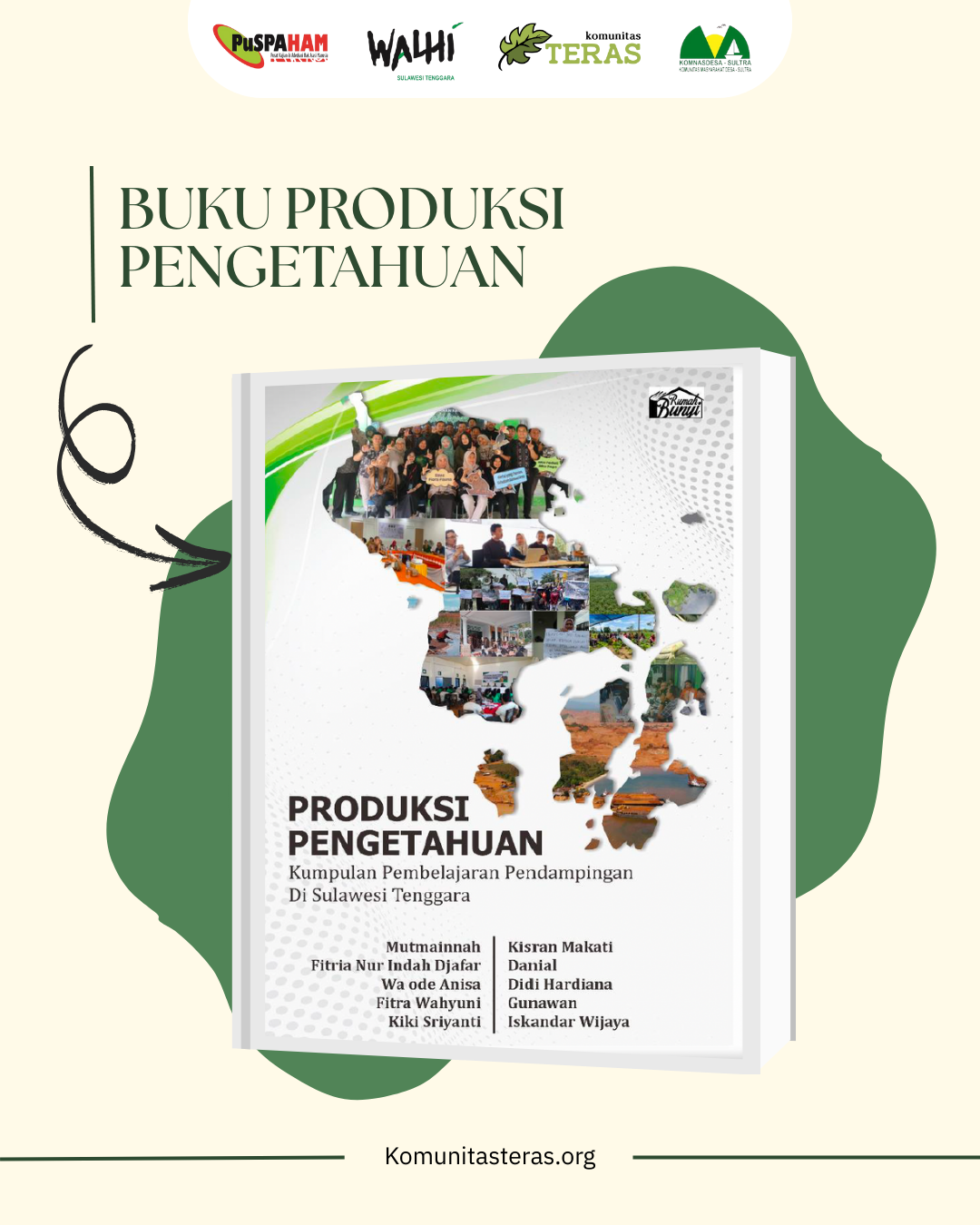



0 Komentar